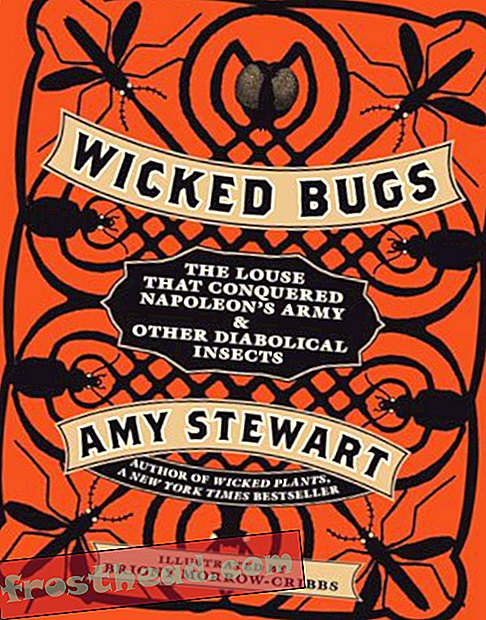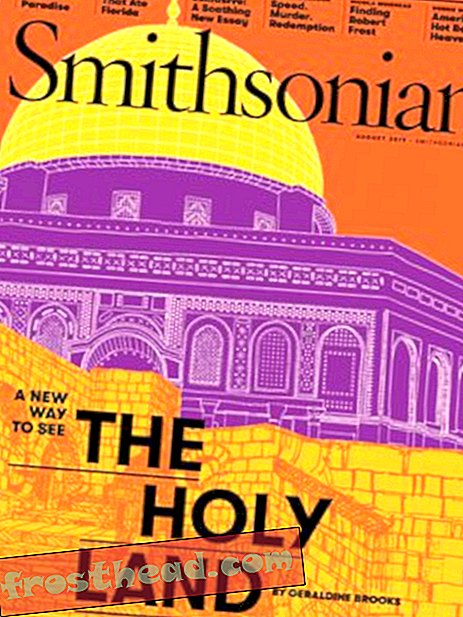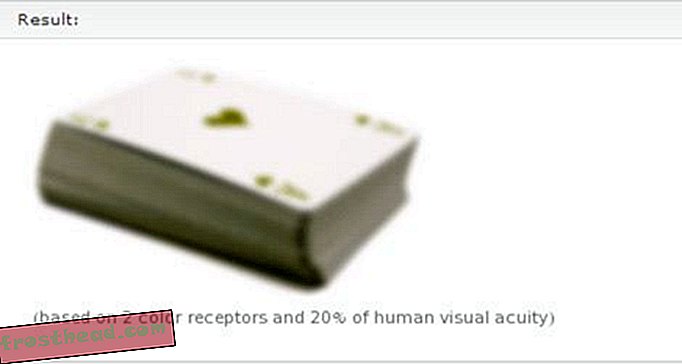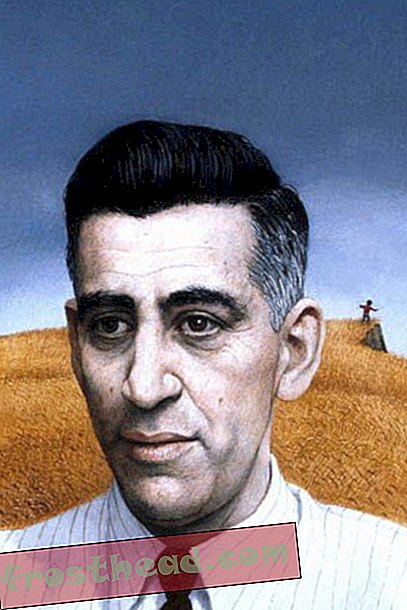Selama berhari-hari saya telah berjalan-jalan di hutan rimba di Papua, Indonesia, dalam upaya untuk mengunjungi anggota suku Korowai, di antara orang-orang terakhir di dunia yang mempraktikkan kanibalisme. Segera setelah cahaya pertama pagi ini saya naik sebuah pirogue, sebuah kano meretas keluar dari batang pohon, untuk tahap terakhir dari perjalanan, di sepanjang Sungai Ndeiram Kabur yang berputar. Sekarang keempat pendayung menekuk punggung mereka dengan kuat, tahu kami akan segera berkemah untuk malam ini.
Pemandu saya, Kornelius Kembaren, telah melakukan perjalanan di antara Korowai selama 13 tahun. Tetapi bahkan dia belum pernah sejauh ini ke hulu, karena, katanya, beberapa Korowai mengancam akan membunuh orang luar yang memasuki wilayah mereka. Beberapa klan dikatakan takut pada kita yang memiliki kulit pucat, dan Kembaren mengatakan banyak Korowai tidak pernah melihat orang kulit putih. Mereka menyebut orang luar laleo ("hantu-setan").
Tiba-tiba, jeritan meletus dari sekitar tikungan. Beberapa saat kemudian, saya melihat sekelompok pria telanjang mengacungkan busur dan anak panah di tepi sungai. Kembaren bergumam kepada tukang perahu untuk berhenti mendayung. "Mereka memerintahkan kita untuk datang ke sisi sungai mereka, " bisiknya padaku. "Kelihatannya buruk, tapi kita tidak bisa melarikan diri. Mereka dengan cepat menangkap kita jika kita mencoba."
Saat keributan orang-orang kesukuan itu terdengar di telingaku, pirogue kami meluncur ke sisi seberang sungai. "Kami tidak ingin melukaimu, " teriak Kembaren dalam Bahasa Indonesia, yang diterjemahkan oleh salah seorang awak perahu kami ke Korowai. "Kami datang dengan damai." Kemudian dua anggota suku menyelinap ke dalam pirogue dan mulai mendayung ke arah kami. Ketika mereka dekat, saya melihat bahwa panah mereka berduri. "Tetap tenang, " kata Kembaren lembut.
Kanibalisme dipraktikkan di antara manusia prasejarah, dan itu bertahan hingga abad ke-19 di beberapa budaya Pasifik Selatan yang terisolasi, terutama di Fiji. Tetapi hari ini Korowai adalah satu dari sedikit suku yang dipercaya memakan daging manusia. Mereka tinggal sekitar 100 mil ke daratan dari Laut Arafura, tempat Michael Rockefeller, putra gubernur New York saat itu Nelson Rockefeller, menghilang pada tahun 1961 ketika mengumpulkan artefak dari suku Papua lainnya; Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sebagian besar Korowai masih hidup dengan sedikit pengetahuan tentang dunia di luar tanah air mereka dan sering bertengkar satu sama lain. Beberapa dikatakan membunuh dan memakan penyihir pria yang mereka sebut khakhua .
Pulau New Guinea, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland, adalah daratan tropis bergunung-gunung yang berpenduduk jarang yang terbagi antara dua negara: negara Papua Nugini yang merdeka di timur, dan provinsi Papua dan Irian Jaya Barat di Indonesia. Barat. Korowai tinggal di Papua bagian tenggara.
Perjalanan saya dimulai di Bali, di mana saya naik pesawat melintasi Laut Banda ke kota Timika di Papua; anak perusahaan perusahaan tambang Amerika, PT Freeport Indonesia, mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbesar di dunia di dekatnya. Gerakan Papua Merdeka, yang terdiri dari beberapa ratus pemberontak yang dilengkapi dengan busur dan anak panah, telah berjuang untuk kemerdekaan dari Indonesia sejak 1964. Karena Indonesia telah melarang wartawan asing mengunjungi provinsi tersebut, saya masuk sebagai turis.
Setelah singgah di Timika, jet kami naik di atas rawa berawa melewati bandara dan menuju ke gunung yang tinggi. Di luar pantai, lereng terjal setinggi 16.500 kaki di atas permukaan laut dan membentang sejauh 400 mil. Menunggu saya di Jayapura, sebuah kota berpenduduk 200.000 di pantai utara dekat perbatasan dengan Papua Nugini, adalah Kembaren, 46, seorang Sumatra yang datang ke Papua mencari petualangan 16 tahun lalu. Dia pertama kali mengunjungi Korowai pada tahun 1993, dan telah mengetahui banyak tentang budaya mereka, termasuk beberapa bahasa mereka. Dia dibalut celana pendek khaki dan sepatu bot trekking, dan tatapannya yang tak tergoyahkan dan rahang sekeras batu memberinya tampilan sersan bor.
Perkiraan terbaik adalah ada sekitar 4.000 Korowai. Secara tradisional, mereka telah tinggal di rumah-rumah pohon, dalam kelompok selusin orang di hutan terbuka; keterikatan mereka pada rumah pohon dan tanah di sekitarnya terletak pada inti identitas mereka, antropolog Smithsonian Institution Paul Taylor mencatat dalam film dokumenter 1994 tentang mereka, Lords of the Garden . Namun, selama beberapa dekade terakhir, beberapa Korowai telah pindah ke pemukiman yang didirikan oleh misionaris Belanda, dan dalam beberapa tahun terakhir, beberapa turis telah berkelana ke tanah Korowai. Tetapi semakin dalam memasuki hutan hujan, semakin sedikit paparan yang dimiliki Korowai terhadap budaya yang asing bagi mereka.
Setelah kami terbang dari Jayapura barat daya ke Wamena, titik awal di dataran tinggi Papua, Korowai muda yang kurus mendekati kami. Dalam Bahasa Indonesia, ia mengatakan bahwa namanya adalah Boas dan bahwa dua tahun yang lalu, ingin melihat kehidupan di luar rumah pohonnya, ia menumpang pada penerbangan charter dari Yaniruma, sebuah pemukiman di tepi wilayah Korowai. Dia telah mencoba untuk pulang, katanya, tetapi tidak ada yang akan membawanya. Boas mengatakan bahwa seorang pemandu yang pulang memberi tahu dia bahwa ayahnya sangat kesal dengan ketidakhadiran putranya sehingga dia dua kali membakar rumah pohonnya sendiri. Kami memberitahunya bahwa ia bisa ikut dengan kami.
Pagi berikutnya delapan dari kita naik Twin Otter, seorang pekerja keras yang lepas landas pendek dan kemampuan mendarat akan membawa kita ke Yaniruma. Begitu kami mengudara, Kembaren menunjukkan kepada saya sebuah peta: garis spidery yang menandai sungai dataran rendah dan ribuan mil persegi hutan hijau. Misionaris Belanda yang datang untuk mengubah Korowai pada akhir 1970-an menyebutnya "neraka di selatan."
Setelah 90 menit kami turun, mengikuti Sungai Ndeiram Kabur yang berliku. Di hutan di bawah, Boas melihat rumah pohon ayahnya, yang tampaknya sangat tinggi dari tanah, seperti sarang burung raksasa. Boas, yang mengenakan topi kuning aster, suvenir “peradaban, ” memelukku dengan rasa terima kasih, dan air mata menetes di pipinya.
Di Yaniruma, sederetan pondok panggung yang didirikan oleh para misionaris Belanda pada tahun 1979, kami membentur tanah yang diukir dari hutan. Sekarang, yang mengejutkan saya, Boas mengatakan ia akan menunda kepulangannya untuk melanjutkan bersama kami, terpikat oleh janji petualangan dengan seorang laleo, dan ia dengan riang mengangkat sekarung bahan makanan ke pundaknya. Ketika pilot melempar Twin Otter kembali ke langit, selusin orang Korowai mengangkat ransel dan persediaan kami dan berjalan dengan susah payah menuju hutan dalam satu file menuju sungai. Sebagian besar membawa busur dan anak panah.
Pdt. Johannes Veldhuizen, seorang misionaris Belanda dengan Misi Gereja Reformed, pertama kali melakukan kontak dengan Korowai pada tahun 1978 dan membatalkan rencana untuk mengubahnya menjadi agama Kristen. "Dewa gunung yang sangat kuat memperingatkan Korowai bahwa dunia mereka akan dihancurkan oleh gempa bumi jika orang luar datang ke tanah mereka untuk mengubah kebiasaan mereka, " katanya kepada saya melalui telepon dari Belanda beberapa tahun yang lalu. "Jadi kami pergi sebagai tamu, bukan sebagai penakluk, dan tidak pernah menekan Korowai untuk mengubah cara mereka." Pdt. Gerrit van Enk, misionaris Belanda lainnya dan penulis bersama Korowai Irian Jaya, menciptakan istilah "garis pasifikasi" untuk perbatasan imajiner yang memisahkan klan Korowai yang terbiasa dengan orang luar dari mereka yang lebih jauh ke utara. Dalam wawancara telepon terpisah dari Belanda, dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak pernah melampaui garis pasifikasi karena kemungkinan bahaya dari klan Korowai di sana memusuhi keberadaan laleo di wilayah mereka.
Ketika kami melewati Yaniruma, saya terkejut bahwa tidak ada petugas kepolisian Indonesia yang meminta izin pemerintah diberikan kepada saya sehingga saya bisa melanjutkan. "Pos polisi terdekat ada di Senggo, beberapa hari lalu di sepanjang sungai, " Kembaren menjelaskan. "Kadang-kadang seorang pekerja medis atau pejabat datang ke sini selama beberapa hari, tetapi mereka terlalu takut untuk pergi jauh ke wilayah Korowai."
Memasuki hutan hujan Korowai seperti melangkah ke gua berair raksasa. Dengan matahari yang cerah di atas kepala aku bernapas dengan mudah, tetapi ketika para portir mendorong menembus semak-semak, tenunan lebat pohon kanopi menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan yang hijau. Panasnya menyengat dan udara menetes dengan kelembapan. Ini adalah tempat dihantui laba-laba raksasa, ular pembunuh, dan mikroba mematikan. Jauh di atas kanopi, burung beo memekik saat aku mengikuti para kuli di sepanjang jalan yang nyaris tak terlihat, berkelok-kelok di sekitar pohon yang basah kuyup dan telapak tangan purba. Kemejaku menempel di punggungku, dan aku sering minum di botol airku. Curah hujan tahunan di sini adalah sekitar 200 inci, menjadikannya salah satu tempat terbasah di bumi. Hujan yang tiba-tiba mengirimkan tetesan hujan menembus celah di kanopi, tetapi kami terus berjalan.
Korowai setempat telah meletakkan kayu di atas lumpur, dan para kuli tanpa alas kaki menyeberanginya dengan mudah. Tapi, berusaha mati-matian untuk menyeimbangkan saat aku menyusuri setiap batang kayu, berkali-kali aku tergelincir, tersandung dan jatuh ke dalam lumpur yang terkadang setinggi pinggang, memar dan menggaruk kaki dan tanganku. Kayu yang licin sepanjang sepuluh meter menjembatani banyak kemiringan di tanah. Beringsut melintas seperti tali pejalan kaki, aku bertanya-tanya bagaimana para kuli akan mengeluarkanku dari hutan seandainya aku jatuh dan patah kaki. "Apa yang aku lakukan di sini?" Saya terus bergumam, meskipun saya tahu jawabannya: Saya ingin bertemu dengan orang-orang yang dikatakan masih mempraktikkan kanibalisme.
Jam mencair menjadi jam saat kami terus maju, berhenti sebentar untuk beristirahat. Dengan malam dekat, hatiku melonjak lega ketika poros cahaya keperakan menyelinap melalui pepohonan di depan: tempat terbuka. "Itu Manggel, " kata Kembaren — desa lain yang didirikan oleh misionaris Belanda. "Kami akan menginap di sini."
Anak-anak Korowai dengan manik-manik di lehernya berlari untuk menunjuk dan terkikik ketika aku berjalan sempoyongan ke desa — beberapa gubuk jerami bertengger di atas panggung dan menghadap ke sungai. Saya perhatikan tidak ada orang tua di sini. "Korowai hampir tidak memiliki obat apa pun untuk memerangi penyakit hutan atau menyembuhkan luka perang, sehingga tingkat kematiannya tinggi, " Kembaren menjelaskan. "Orang jarang hidup sampai usia pertengahan." Seperti yang ditulis van Enk, Korowai secara rutin jatuh ke dalam konflik antar -lan; penyakit, termasuk malaria, TBC, kaki gajah dan anemia, dan apa yang disebutnya "kompleks khakhua." Korowai tidak memiliki pengetahuan tentang kuman mematikan yang menyerang hutan mereka, dan karena itu percaya bahwa kematian misterius harus disebabkan oleh khakhua, atau penyihir yang mengambil bentuk manusia.
Setelah kami makan malam ikan sungai dan nasi, Boas bergabung dengan saya di gubuk dan duduk bersila di lantai jerami, matanya yang gelap memantulkan sinar dari senter saya, satu-satunya sumber cahaya kami. Dengan menggunakan Kembaren sebagai penerjemah, ia menjelaskan mengapa Korowai membunuh dan memakan sesama anggota suku mereka. Itu karena khakhua, yang menyamar sebagai kerabat atau teman orang yang ingin dia bunuh. "Khakhua memakan bagian dalam korban ketika dia tidur, " Boas menjelaskan, "menggantikannya dengan abu perapian sehingga korban tidak tahu dia sedang dimakan. Khakhua akhirnya membunuh orang itu dengan menembakkan panah ajaib ke dalam hatinya." Ketika seorang anggota klan meninggal, kerabat dan teman prianya merebut dan membunuh khakhua. "Biasanya, korban yang [sekarat] membisikkan kepada kerabatnya nama orang yang dia kenal adalah khakhua, " kata Boas. "Dia mungkin dari rumah pohon yang sama atau yang lain."
Saya bertanya kepada Boas apakah Korowai memakan orang karena alasan lain atau memakan tubuh musuh yang telah mereka bunuh dalam pertempuran. "Tentu saja tidak, " jawabnya, menatapku lucu. "Kami tidak makan manusia, kami hanya makan khakhua."
Pembunuhan dan makan khakhua dilaporkan telah menurun di kalangan warga suku di dan dekat pemukiman. Rupert Stasch, seorang antropolog di Reed College di Portland, Oregon, yang telah tinggal di Korowai selama 16 bulan dan mempelajari budaya mereka, menulis dalam jurnal Oceania bahwa Korowai mengatakan bahwa mereka telah "menyerah" membunuh penyihir sebagian karena mereka semakin mendua tentang penyihir. praktik dan sebagian sebagai reaksi terhadap beberapa insiden dengan polisi. Dalam satu di awal 90-an, Stasch menulis, seorang pria Yaniruma membunuh suami saudara perempuannya karena menjadi khakhua. Polisi menangkap si pembunuh, kaki tangan dan seorang kepala desa. "Polisi menggulingkan mereka dalam tong, membuat mereka berdiri semalam di kolam penuh lintah, dan memaksa mereka makan tembakau, cabai, kotoran hewan, dan pepaya mentah, " tulisnya. Kata-kata perlakuan seperti itu, dikombinasikan dengan ambivalensi Korowais sendiri, mendorong beberapa orang untuk membatasi pembunuhan penyihir bahkan di tempat-tempat di mana polisi tidak berani.
Tetap saja, makan khakhua tetap ada, menurut pemandu saya, Kembaren. "Banyak khakhua dibunuh dan dimakan setiap tahun, " katanya, mengutip informasi yang katanya diperoleh dari berbicara dengan Korowai yang masih tinggal di rumah pohon.
Pada hari ketiga kami trekking, setelah hiking dari segera setelah matahari terbit hingga senja, kami mencapai Yafufla, barisan pondok panggung yang didirikan oleh para misionaris Belanda. Malam itu, Kembaren membawaku ke gubuk terbuka yang menghadap ke sungai, dan kami duduk di dekat api unggun kecil. Dua laki-laki mendekat melalui kegelapan, satu dengan celana pendek, yang lain telanjang untuk kalung dari gigi babi yang berharga dan sehelai daun yang membungkus ujung penisnya. "Itu Kilikili, " bisik Kembaren, "pembunuh khakhua yang paling terkenal." Kilikili membawa busur dan panah berduri. Matanya kosong dari ekspresi, bibirnya tersering menyeringai dan dia berjalan tanpa suara seperti bayangan.
Pria lain, yang ternyata adalah saudara laki-laki Kilikili, Bailom, menarik tengkorak manusia dari sebuah tas. Lubang yang bergerigi membentuk dahi. "Ini Bunop, khakhua paling baru yang dia bunuh, " kata Kembaren tentang tengkorak itu. "Bailom menggunakan kapak batu untuk membelah tengkorak untuk membuka otak." Mata panduan itu redup. "Dia adalah salah satu portir terbaik saya, seorang pemuda yang ceria, " katanya.
Bailom memberikan tengkorak itu padaku. Saya tidak ingin menyentuhnya, tetapi saya juga tidak ingin menyinggung perasaannya. Darahku menggigil karena merasakan tulang telanjang. Saya telah membaca cerita dan menonton film dokumenter tentang Korowai, tetapi sejauh yang saya tahu tidak ada wartawan dan pembuat film yang pergi sejauh hulu seperti yang akan kami habiskan, dan tidak ada yang saya tahu pernah melihat tengkorak khakhua.
Refleksi api berkedip-kedip di wajah saudara-saudara ketika Bailom memberi tahu saya bagaimana dia membunuh khakhua, yang tinggal di Yafufla, dua tahun lalu. "Tepat sebelum sepupu saya meninggal, dia memberi tahu saya bahwa Bunop adalah seorang khakhua dan memakannya dari dalam, " katanya, dengan terjemahan Kembaren. "Jadi kami menangkapnya, mengikatnya dan membawanya ke sungai, di mana kami menembakkan panah padanya."
Bailom mengatakan bahwa Bunop berteriak minta ampun sepanjang jalan, memprotes bahwa dia bukan seorang khakhua. Tapi Bailom tidak goyah. "Sepupu saya hampir mati ketika dia memberi tahu saya dan tidak akan berbohong, " kata Bailom.
Di sungai, kata Bailom, ia menggunakan kapak batu untuk memenggal kepala khakhua. Saat dia memegangnya di udara dan memalingkannya dari tubuh, yang lain meneriakkan dan memotong-motong tubuh Bunop. Bailom, membuat gerakan memotong dengan tangannya, menjelaskan: "Kami memotong ususnya dan membuka tulang rusuk, memotong lengan kanan yang melekat pada tulang rusuk kanan, lengan kiri dan tulang rusuk kiri, dan kemudian kedua kaki."
Bagian-bagian tubuh, katanya, secara individual dibungkus dengan daun pisang dan didistribusikan di antara anggota klan. "Tapi saya tetap kepala karena itu milik keluarga yang membunuh khakhua, " katanya. "Kami memasak daging seperti kami memasak babi, menempatkan daun kelapa di atas daging yang dibungkus bersama dengan membakar batu sungai panas untuk membuat uap."
Beberapa pembaca mungkin percaya bahwa kedua orang ini sedang melibatkan saya — bahwa mereka hanya memberi tahu pengunjung apa yang ingin dia dengar — dan bahwa tengkorak itu berasal dari seseorang yang meninggal karena sebab lain. Tapi saya yakin mereka mengatakan yang sebenarnya. Saya menghabiskan delapan hari bersama Bailom, dan semua yang dia katakan terbukti faktual. Saya juga memeriksa dengan empat lelaki Yafufla lain yang mengatakan mereka bergabung dalam pembunuhan, pembongkaran dan makan Bunop, dan perincian rekening mereka mencerminkan laporan kanibalisme khakhua oleh misionaris Belanda yang tinggal di Korowai selama beberapa tahun. Kembaren jelas menerima kisah Bailom sebagai fakta.
Di sekitar api unggun kami, Bailom memberitahuku bahwa ia tidak merasa menyesal. "Balas dendam adalah bagian dari budaya kita, jadi ketika khakhua memakan seseorang, orang-orang memakan khakhua, " katanya. (Taylor, antropolog Smithsonian Institution, menggambarkan makan khakhua sebagai "bagian dari sistem keadilan.") "Ini normal, " kata Bailom. "Aku tidak merasa sedih telah membunuh Bunop, meskipun dia adalah seorang teman."
Dalam cerita rakyat kanibal, diceritakan dalam banyak buku dan artikel, daging manusia dikatakan dikenal sebagai "babi panjang" karena rasanya yang serupa. Ketika saya menyebutkan ini, Bailom menggelengkan kepalanya. "Daging manusia rasanya seperti kasuari muda, " katanya, merujuk pada burung mirip burung unta setempat. Saat makan khakhua, katanya, baik pria maupun wanita — anak-anak tidak hadir — makan semuanya kecuali tulang, gigi, rambut, kuku, kuku dan kuku serta penis. "Aku suka rasa semua bagian tubuh, " kata Bailom, "tapi otak adalah kesukaanku." Kilikili mengangguk setuju, tanggapan pertamanya sejak dia tiba.
Ketika khakhua adalah anggota dari klan yang sama, ia diikat dengan rotan dan menempuh perjalanan sehari ke sungai di dekat rumah pohon klan yang ramah. "Ketika mereka menemukan khakhua yang terlalu dekat hubungannya dengan mereka untuk dimakan, mereka membawanya kepada kita sehingga kita dapat membunuh dan memakannya, " kata Bailom.
Dia mengatakan dia secara pribadi telah membunuh empat khakhua. Dan Kilikili? Bailom tertawa. "Dia bilang dia akan memberitahumu sekarang nama 8 khakhua yang dia bunuh, " jawabnya, "dan jika kamu datang ke rumah pohonnya di hulu, dia akan memberitahumu nama-nama 22 khakhua yang lain."
Saya bertanya apa yang mereka lakukan dengan tulang-tulang itu.
"Kami menempatkan mereka di jalur yang mengarah ke pembukaan rumah pohon, untuk memperingatkan musuh-musuh kami, " kata Bailom. "Tapi si pembunuh bisa menjaga tengkoraknya. Setelah kita makan khakhua, kita memukul dengan keras di dinding rumah pohon kita sepanjang malam dengan tongkat" untuk memperingatkan khakhua lain agar menjauh.
Ketika kami berjalan kembali ke gubuk kami, Kembaren mengaku bahwa "bertahun-tahun yang lalu, ketika saya berteman dengan Korowai, seorang pria di Yafufla mengatakan kepada saya bahwa saya harus makan daging manusia jika mereka mempercayai saya. Dia memberi saya sebuah chunk, "katanya. "Itu agak sulit tetapi rasanya enak."
Malam itu aku butuh waktu lama untuk bisa tidur.









 tulang khakhua (penyihir) ditempatkan di jalan untuk memperingatkan musuh-musuh mereka. (Kornelius Kembaren menunjuk ke tengkorak khakhua.) (Paul Raffaele)
tulang khakhua (penyihir) ditempatkan di jalan untuk memperingatkan musuh-musuh mereka. (Kornelius Kembaren menunjuk ke tengkorak khakhua.) (Paul Raffaele)  (Paul Raffaele)
(Paul Raffaele)  Kilikili (dengan tengkorak yang katanya berasal dari khakhua) mengatakan bahwa dia telah membunuh tidak kurang dari 30 khakhua. (Paul Raffaele)
Kilikili (dengan tengkorak yang katanya berasal dari khakhua) mengatakan bahwa dia telah membunuh tidak kurang dari 30 khakhua. (Paul Raffaele)  Setelah orang tuanya meninggal, Wawa, 6, dituduh oleh anggota klannya sebagai seorang khakhua. Pamannya mengambil anak itu dari rumah pohonnya untuk tinggal di pemukiman. (Paul Raffaele)
Setelah orang tuanya meninggal, Wawa, 6, dituduh oleh anggota klannya sebagai seorang khakhua. Pamannya mengambil anak itu dari rumah pohonnya untuk tinggal di pemukiman. (Paul Raffaele)  "Aku tahu kamu sama seperti kita, " kata Lepeadon (kanan) kepada penulis setelah menerimanya di rumah pohon klan Letin. (Paul Raffaele)
"Aku tahu kamu sama seperti kita, " kata Lepeadon (kanan) kepada penulis setelah menerimanya di rumah pohon klan Letin. (Paul Raffaele)  Tiga hari kemudian, para pengunjung memulai perjalanan kembali ke hilir. (Paul Raffaele)
Tiga hari kemudian, para pengunjung memulai perjalanan kembali ke hilir. (Paul Raffaele)  Khanduop mengucapkan selamat tinggal kepada putranya, Boas (bertopi), ketika pemuda itu pergi untuk tinggal di pemukiman. (Paul Raffaele)
Khanduop mengucapkan selamat tinggal kepada putranya, Boas (bertopi), ketika pemuda itu pergi untuk tinggal di pemukiman. (Paul Raffaele)  Penulis menolak sarapan katak dan serangga yang dibawa kepadanya oleh empat wanita Korowai. Bekas luka melingkar mereka adalah tanda kecantikan yang dibuat dengan bara bara. (Paul Raffaele)
Penulis menolak sarapan katak dan serangga yang dibawa kepadanya oleh empat wanita Korowai. Bekas luka melingkar mereka adalah tanda kecantikan yang dibuat dengan bara bara. (Paul Raffaele)  Cara hidup tradisional, dicontohkan oleh Lepeadon (paling kiri) dan rumah pohon klan Letin, masih berlaku di daerah yang lebih terpencil di wilayah Korowai. Tapi itu berubah ke arah hilir, karena beberapa warga suku bergerak bolak-balik antara rumah pohon dan pemukiman mereka. (Paul Raffaele)
Cara hidup tradisional, dicontohkan oleh Lepeadon (paling kiri) dan rumah pohon klan Letin, masih berlaku di daerah yang lebih terpencil di wilayah Korowai. Tapi itu berubah ke arah hilir, karena beberapa warga suku bergerak bolak-balik antara rumah pohon dan pemukiman mereka. (Paul Raffaele) Keesokan paginya Kembaren membawa ke pondok seorang anak lelaki berusia 6 tahun bernama Wawa, yang telanjang kecuali kalung manik-manik. Berbeda dengan anak-anak desa lainnya, riuh dan tersenyum, Wawa ditarik dan matanya tampak sangat sedih. Kembaren memeluknya. “Ketika ibu Wawa meninggal November lalu — saya pikir dia menderita TB, dia sangat sakit, batuk dan sakit — orang-orang di rumah pohonnya mencurigainya sebagai seorang khakhua, ” katanya. "Ayahnya meninggal beberapa bulan sebelumnya, dan mereka percaya [Wawa] menggunakan sihir untuk membunuh mereka berdua. Keluarganya tidak cukup kuat untuk melindunginya di rumah pohon, sehingga Januari ini pamannya melarikan diri dengan Wawa, membawanya ke sini, di mana keluarga lebih kuat. " Apakah Wawa tahu ancaman yang dia hadapi? "Dia sudah mendengarnya dari kerabatnya, tapi kurasa dia tidak sepenuhnya mengerti bahwa orang-orang di rumah pohonnya ingin membunuh dan memakannya, meskipun mereka mungkin akan menunggu sampai dia lebih tua, sekitar 14 atau 15, sebelum mereka mencoba. Tapi sementara dia tinggal di Yafufla, dia seharusnya aman. "
Segera para kuli menimbun peralatan kami dan menuju hutan. "Kami mengambil jalan yang mudah, dengan pirogue, " Kembaren memberitahuku. Bailom dan Kilikili, masing-masing memegang busur dan anak panah, telah bergabung dengan portir. "Mereka tahu klan di hulu lebih baik daripada orang-orang Yaniruma kita, " Kembaren menjelaskan.
Bailom menunjukkan kepadaku panah-panahnya, masing-masing poros sepanjang satu yard yang diikat dengan sulur ke panah yang dirancang untuk mangsa tertentu. Panah panah babi, katanya, berbilah lebar; untuk burung, panjang dan sempit. Mata panah ikan ditekuk, sedangkan mata panah untuk manusia masing-masing adalah sebatang tangan tulang kasuari dengan enam atau lebih duri yang diukir di setiap sisi — untuk memastikan kerusakan yang mengerikan ketika dipotong dari daging korban. Noda darah gelap melapisi panah ini.
Saya bertanya pada Kembaren apakah dia nyaman dengan gagasan dua kanibal yang menyertai kami. "Sebagian besar kuli mungkin telah memakan daging manusia, " jawabnya sambil tersenyum.
Kembaren membawa saya ke Sungai Ndeiram Kabur, tempat kami menaiki pirogue yang panjang dan ramping. Aku duduk di tengah, sisi-sisi menekan tubuhku. Dua dayung Korowai berdiri di buritan, dua lagi di haluan, dan kami mendorong, kemudi dekat dengan tepi sungai, di mana aliran air paling lambat. Setiap kali tukang perahu manuver pirogue di sekitar gundukan pasir, arus yang kuat di tengah sungai mengancam untuk membuat kita jungkir balik. Mendayung ke hulu sangat sulit, bahkan bagi para tukang perahu yang berotot, dan mereka sering mendobrak lagu Korowai yang bertepatan dengan tamparan dayung di atas air, nyanyian yodeling yang bergema di sepanjang tepi sungai.
Tirai pohon hijau tinggi yang ditenun dengan pita pohon anggur kusut melindungi hutan. Teriakan sirene jangkrik menembus udara. Hari berlalu dengan kabur, dan malam turun dengan cepat.
Dan saat itulah kita disapa oleh orang-orang yang berteriak di tepi sungai. Kembaren menolak untuk datang ke sisi sungai mereka. "Terlalu berbahaya, " bisiknya. Sekarang dua Korowai yang dipersenjatai dengan busur dan anak panah mengayuh pirogue ke arah kami. Saya bertanya kepada Kembaren apakah dia punya senjata. Dia menggelengkan kepalanya.
Ketika pirogue mereka menabrak kita, salah satu dari mereka menggeram bahwa laleo dilarang memasuki sungai suci mereka, dan bahwa kehadiranku membuat marah para roh. Korowai adalah penganut animisme, percaya bahwa makhluk yang kuat hidup di pohon-pohon tertentu dan bagian-bagian sungai. Anggota suku menuntut agar kami memberi klan babi untuk membebaskan penistaan. Seekor babi berharga 350.000 rupiah, atau sekitar $ 40. Ini adalah penggeledahan Zaman Batu. Saya menghitung uang itu dan memberikannya kepada lelaki itu, yang melirik mata uang Indonesia dan memberikan kami izin untuk lulus.
Apa gunanya uang untuk orang-orang ini? Saya meminta Kembaren sebagai pendayung perahu dayung kami ke hulu yang aman. "Tidak ada gunanya di sini, " jawabnya, "tetapi setiap kali mereka mendapatkan uang, dan itu jarang terjadi, klan menggunakannya untuk membantu membayar harga pengantin untuk gadis-gadis Korowai yang tinggal lebih dekat dengan Yaniruma. Mereka memahami bahaya inses, dan karenanya gadis harus menikah menjadi klan yang tidak terkait. "
Kira-kira satu jam lebih jauh ke atas sungai, kami berhenti di tepi sungai, dan aku memanjat lereng berlumpur, menyeret diriku di atas lereng yang licin dengan menggenggam akar pohon yang terbuka. Bailom dan para kuli menunggu kami dan mengenakan wajah khawatir. Bailom mengatakan bahwa anggota suku tahu kami akan datang karena mereka telah mencegat para kuli saat mereka lewat di dekat rumah pohon mereka.
Apakah mereka benar-benar akan membunuh kita jika kita tidak membayar? Saya bertanya kepada Bailom, melalui Kembaren. Bailom mengangguk: "Mereka akan membiarkanmu lewat malam ini karena mereka tahu kau harus kembali ke hilir. Lalu, mereka akan menyergapmu, beberapa panah menembak dari tepi sungai dan yang lainnya menyerang dari jarak dekat dengan pirogue mereka."
Para porter merangkai semua kecuali satu terpal di atas persediaan kami. Tempat berlindung kami untuk malam ini adalah empat tiang yang dipasang di sebuah kotak yang berjarak sekitar empat meter dan ditutup oleh terpal dengan sisi terbuka. Segera setelah tengah malam hujan deras membasahi kami. Angin membuat gigiku gemeletuk, dan aku duduk dengan sedih memeluk lututku. Melihatku menggigil, Boas menarik tubuhku ke tubuhnya agar hangat. Ketika saya tertidur, sangat lelah, saya memiliki pemikiran yang paling aneh: ini adalah pertama kalinya saya tidur dengan kanibal.
Kami pergi pada cahaya pertama, masih basah kuyup. Pada tengah hari pirogue kami mencapai tujuan kami, tepi sungai dekat dengan rumah pohon, atau khaim, dari klan Korowai yang Kembaren katakan belum pernah melihat orang kulit putih. Portir kami tiba di depan kami dan telah membangun gubuk yang belum sempurna. "Saya mengirim seorang teman Korowai ke sini beberapa hari yang lalu untuk meminta klan mengizinkan kami mengunjungi mereka, " kata Kembaren. "Kalau tidak, mereka akan menyerang kita."
Saya bertanya mengapa mereka memberi izin bagi seorang laleo untuk memasuki tanah suci mereka. "Aku pikir mereka sama penasarannya denganmu, si hantu-iblis, sama seperti kamu melihat mereka, " jawab Kembaren.
Pada tengah hari, Kembaren dan saya mendaki 30 menit melalui hutan lebat dan mengarungi sungai yang dalam. Dia menunjuk ke depan ke rumah pohon yang terlihat sepi. Itu bertengger di pohon beringin yang dipenggal, lantainya berupa kisi-kisi kayu dan potongan kayu. Sekitar sepuluh yard dari tanah. "Itu milik klan Letin, " katanya. Korowai dibentuk menjadi apa yang oleh para antropolog disebut patriclan, yang mendiami tanah leluhur dan melacak kepemilikan dan silsilah melalui garis lelaki.
Seekor kasuari muda lewat, mungkin binatang peliharaan keluarga. Seekor babi besar, memerah dari tempat persembunyiannya di rumput, berlari ke dalam hutan. "Di mana Korowai?" Aku bertanya. Kembaren menunjuk ke rumah pohon. "Mereka sedang menunggu kita."
Aku bisa mendengar suara-suara ketika aku memanjat tiang yang hampir vertikal berlekuk pijakan. Bagian dalam rumah pohon dilingkari kabut asap yang disewa oleh sinar matahari. Para pria muda berkumpul di lantai dekat pintu masuk. Asap dari perapian perapian telah melapisi dinding kulit dan langit-langit daun sagu, membuat gubuk tersebut berbau tidak sedap. Sepasang kapak batu, beberapa busur dan panah, serta kantung jaring dimasukkan ke dalam kasau yang rindang. Lantai berderit saat aku duduk dengan kaki menyilang.
Empat wanita dan dua anak duduk di belakang rumah pohon, para wanita membuat tas dari tanaman merambat dan dengan rajin mengabaikan saya. "Pria dan wanita tinggal di sisi yang berbeda dari rumah pohon dan memiliki perapian sendiri, " kata Kembaren. Setiap perapian terbuat dari potongan-potongan rotan berlapis tanah liat yang ditangguhkan di atas lubang di lantai sehingga bisa dengan cepat dipenggal, jatuh ke tanah, jika api mulai membakar di luar kendali.
Seorang pria paruh baya dengan tubuh berotot dan wajah bulldog mengangkangi garis pemisah gender. Berbicara melalui Boas, Kembaren membuat obrolan kecil tentang tanaman, cuaca, dan pesta-pesta sebelumnya. Pria itu memegang busur dan anak panahnya dan menghindari tatapanku. Tapi sesekali aku menangkapnya mencuri pandang ke arahku. "Itu Lepeadon, khen -mengga-abül klan, atau 'pria galak, '" kata Kembaren. Pria sengit memimpin klan dalam perkelahian. Lepeadon melihat ke tugas itu.
"Klan yang terdiri dari enam pria, empat wanita, tiga pria dan dua wanita tinggal di sini, " kata Kembaren. "Yang lain datang dari rumah pohon terdekat untuk melihat laleo pertama mereka."
Setelah satu jam berbicara, lelaki ganas itu bergerak mendekatiku dan, masih tersenyum, berbicara. "Aku tahu kamu datang dan berharap melihat hantu, tapi sekarang aku melihat kamu seperti kita, manusia, " katanya, ketika Boas menerjemahkan ke Kembaren dan Kembaren menerjemahkan ke saya.
Seorang anak muda mencoba menarik celanaku, dan dia hampir berhasil di tengah badai tawa. Aku ikut tertawa, tetapi tetap memegangi kesederhanaanku. Pdt. Johannes Veldhuizen memberi tahu saya bahwa Korowai yang dia temui telah menganggapnya setan-hantu sampai mereka memata-matai dia mandi di sungai dan melihat bahwa dia datang dilengkapi dengan semua bagian yang diperlukan dari sebuah yanop, atau manusia. Korowai tampaknya sulit memahami pakaian. Mereka menyebutnya laleo-khal, "kulit setan-setan, " dan Veldhuizen mengatakan kepada saya bahwa mereka percaya kemeja dan celananya adalah epidermis ajaib yang bisa ia donasikan atau hapus sesuka hati.
"Kita seharusnya tidak terlalu lama mendorong rapat pertama, " Kembaren memberitahuku saat dia bangkit untuk pergi. Lepeadon mengikuti kami ke tanah dan meraih kedua tanganku. Dia mulai melompat-lompat dan melantunkan, " nemayokh " ("teman"). Aku mengikutinya dalam apa yang tampak sebagai perpisahan ritual, dan dia dengan cepat meningkatkan langkahnya sampai hingar bingar, sebelum dia tiba-tiba berhenti, membuatku terengah-engah.
"Aku belum pernah melihat itu sebelumnya, " kata Kembaren. "Kami baru saja mengalami sesuatu yang sangat istimewa." Itu jelas istimewa bagi saya. Dalam empat dekade perjalanan di antara suku-suku terpencil, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan klan yang jelas tidak pernah melihat orang yang berkulit terang seperti saya. Terpesona, saya menemukan mata saya robek ketika kami kembali ke gubuk kami.
Keesokan paginya, empat wanita Korowai tiba di gubuk kami membawa seekor katak hijau yang berkotek, beberapa belalang dan seekor laba-laba yang menurut mereka baru saja mereka tangkap di hutan. "Mereka sudah membawakan sarapanmu, " kata Boas, tersenyum ketika kata kerjanya diterjemahkan. Dua tahun di sebuah kota di Papua telah mengajarinya bahwa kita bisa mengerutkan hidung kita di makanan lezat Korowai. Para wanita muda memiliki bekas luka melingkar seukuran koin besar sepanjang lengan mereka, di sekitar perut dan di payudara mereka. "Tanda itu membuat mereka terlihat lebih cantik, " kata Boas.
Dia menjelaskan bagaimana mereka dibuat, mengatakan potongan melingkar bara kulit ditempatkan di kulit. Tampaknya cara yang aneh untuk menambah keindahan pada bentuk perempuan, tetapi tidak lebih aneh dari tato, sepatu tumit stiletto, suntikan Botox atau kebiasaan Cina kuno yang secara perlahan menghancurkan tulang kaki bayi perempuan untuk membuat kaki mereka sekecil itu. mungkin.
Kembaren dan saya menghabiskan pagi hari berbicara dengan Lepeadon dan para pemuda tentang agama Korowai. Melihat roh di alam, mereka menemukan kepercayaan pada tuhan tunggal yang membingungkan. Tetapi mereka juga mengenali roh yang kuat, bernama Ginol, yang menciptakan dunia saat ini setelah menghancurkan empat sebelumnya. Selama ingatan kesukuan kembali, para penatua yang duduk di sekitar api telah memberi tahu yang lebih muda bahwa iblis-hantu putih berkulit putih suatu hari akan menyerang tanah Korowai. Setelah laleo tiba, Ginol akan melenyapkan dunia kelima ini. Tanah itu akan pecah, akan ada api dan guntur, dan gunung-gunung akan jatuh dari langit. Dunia ini akan hancur, dan yang baru akan menggantikannya. Nubuat itu, dengan cara tertentu, pasti akan dipenuhi ketika Korowai muda bergerak di antara rumah pohon mereka dan pemukiman hulu, yang membuatku sedih ketika aku kembali ke gubuk kami untuk malam itu.
Korowai, percaya bahwa roh-roh jahat paling aktif di malam hari, biasanya tidak berani keluar dari rumah pohon mereka setelah matahari terbenam. Mereka membagi hari menjadi tujuh periode yang berbeda — fajar, matahari terbit, tengah hari, siang, sore, malam dan malam. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk menghitung angka. Lepeadon menunjukkan kepadaku caranya, dengan mencentang jari-jari tangan kirinya, lalu menyentuh pergelangan tangan, lengan, siku, lengan atas, bahu, leher, telinga, dan mahkota kepala, dan bergerak ke bawah ke lengan lainnya. Penghitungannya menjadi 25. Untuk hal yang lebih besar dari itu, Korowai memulai kembali dan menambahkan kata laifu, yang berarti "berbaliklah."
Pada sore hari saya pergi dengan klan ke ladang palem sagu untuk memanen makanan pokok mereka. Dua lelaki merobohkan pohon sagu, masing-masing dengan kapak tangan yang terbuat dari sepotong batu hitam keras dan seukuran kepalan tangan yang tajam di ujungnya dan diikat dengan sulur ke tangkai kayu tipis. Para lelaki kemudian memukul-mukul empulur sagu menjadi bubur kertas, yang diiris perempuan dengan air untuk menghasilkan adonan yang mereka cetak menjadi potongan-potongan kecil dan panggangan.
Seekor ular yang jatuh dari telapak tangan jatuh dengan cepat terbunuh. Lepeadon then loops a length of rattan about a stick and rapidly pulls it to and fro next to some shavings on the ground, producing tiny sparks that start a fire. Blowing hard to fuel the growing flame, he places the snake under a pile of burning wood. When the meat is charred, I'm offered a piece of it. It tastes like chicken.
On our return to the treehouse, we pass banyan trees, with their dramatic, aboveground root flares. The men slam their heels against these appendages, producing a thumping sound that travels across the jungle. "That lets the people at the treehouse know they're coming home, and how far away they are, " Kembaren tells me.
My three days with the clan pass swiftly. When I feel they trust me, I ask when they last killed a khakhua. Lepeadon says it was near the time of the last sago palm feast, when several hundred Korowai gathered to dance, eat vast quantities of sago palm maggots, trade goods, chant fertility songs and let the marriage-age youngsters eye one another. According to our porters, that dates the killing to just over a year ago.
Lepeadon tells Boas he wants me to stay longer, but I have to return to Yaniruma to meet the Twin Otter. As we board the pirogue, the fierce man squats by the riverside but refuses to look at me. When the boatmen push away, he leaps up, scowls, thrusts a cassowary-bone arrow across his bow, yanks on the rattan string and aims at me. After a few moments, he smiles and lowers the bow—a fierce man's way of saying goodbye.
Pada tengah hari, para tukang perahu mengarahkan pirogue ke tepi hutan rawa dan mengikatnya ke batang pohon. Boas melompat keluar dan memimpin jalan, mengatur langkah cepat. Setelah perjalanan satu jam, saya mencapai tanah terbuka seukuran dua lapangan sepak bola dan ditanami pohon pisang. Mendominasi itu adalah rumah pohon yang menjulang sekitar 75 kaki ke langit. Lantai pegasnya bertumpu pada beberapa tiang alami, pohon-pohon tinggi terpotong pada titik di mana dahan-dahannya berkobar.
Boas sedang menunggu kita. Di sebelahnya berdiri ayahnya, Khanduop, seorang pria paruh baya yang mengenakan strip rotan di pinggangnya dan sehelai daun yang menutupi bagian penisnya. Dia meraih tangan saya dan mengucapkan terima kasih karena membawa pulang putranya. Dia telah membunuh seekor babi besar untuk kesempatan itu, dan Bailom, dengan apa yang menurut saya menjadi kekuatan manusia super, membawanya di punggungnya dengan tiang berlekuk ke dalam rumah pohon. Di dalam, setiap sudut dan celah dipenuhi dengan tulang-tulang dari pesta-pesta sebelumnya — kerangka ikan berduri, rahang babi blockbuster, tengkorak rubah dan tikus terbang. Tulang-tulang itu menjuntai bahkan dari kait yang digantung di sepanjang langit-langit, dekat buntalan banyak burung beo berwarna-warni dan bulu kasuari. Korowai percaya bahwa dekorasi menandakan keramahan dan kemakmuran.
Saya bertemu Yakor, seorang suku tinggi, bermata baik dari hulu pohon, yang berjongkok di dekat api bersama Khanduop, Bailom dan Kilikili. Ibu Boas sudah meninggal, dan Khanduop, seorang lelaki ganas, telah menikahi saudara perempuan Yakor. Ketika pembicaraan beralih ke makanan khakhua yang telah mereka nikmati, mata Khanduop berbinar. Dia makan di banyak khakhua, katanya, dan rasanya adalah yang paling enak dari semua makhluk yang pernah dia makan.
Pagi berikutnya para kuli berangkat ke sungai, membawa barang-barang kami yang tersisa. Tetapi sebelum saya pergi, Khanduop ingin berbicara; putranya dan Kembaren menerjemahkan. "Boas sudah memberitahuku dia akan tinggal di Yaniruma bersama saudaranya, kembali hanya untuk berkunjung, " gumamnya. Tatapan mata Khanduop. "Waktu Korowai yang sebenarnya akan segera berakhir, dan itu membuatku sangat sedih."
Boas tersenyum lemah pada ayahnya dan berjalan bersamaku ke pirogue untuk perjalanan dua jam ke Yaniruma, mengenakan topi kuningnya seolah itu adalah visa untuk abad ke-21.
Tiga tahun sebelumnya saya telah mengunjungi Korubo, suku asli yang terisolasi di Amazon, bersama dengan Sydney Possuelo, yang saat itu menjadi direktur Departemen Brasil untuk Orang Indian Terisolasi [SMITHSONIAN, April 2005]. Pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan orang-orang semacam itu — apakah akan menarik mereka ke masa kini atau membiarkan mereka tidak tersentuh di hutan dan tradisi mereka — telah membuat Possuelo bermasalah selama beberapa dekade. "Saya percaya kita harus membiarkan mereka hidup di dunia khusus mereka sendiri, " katanya kepada saya, "karena begitu mereka pergi ke hulu ke pemukiman dan melihat apa yang bagi mereka keajaiban dan keajaiban hidup kita, mereka tidak pernah kembali hidup dalam cara tradisional."
Begitu pula dengan Korowai. Mereka memiliki paling banyak satu generasi yang tersisa dalam budaya tradisional mereka — budaya yang mencakup praktik-praktik yang diakui membuat kita membenci. Tahun demi tahun para pemuda dan pemudi akan pindah ke Yaniruma dan permukiman-permukiman lain sampai hanya anggota klan yang sudah lanjut usia yang tersisa di rumah-rumah pohon. Dan pada saat itu ramalan saleh Ginol akan mencapai penggenapan apokaliptiknya, dan guntur dan gempa bumi sejenis akan menghancurkan dunia Korowai lama selamanya.