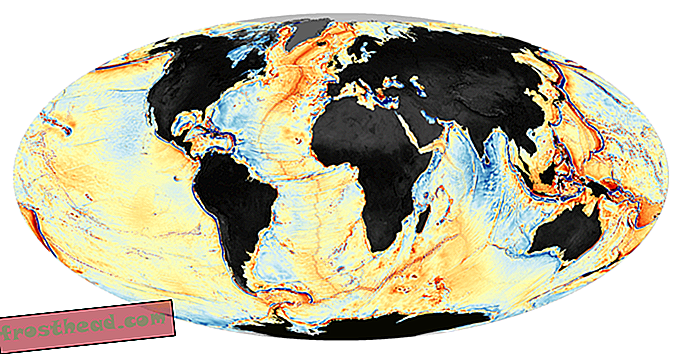Dengan tubuh kecil berbulu dan mata ingin tahu yang besar, lemur tikus abu-abu bisa tampak seperti persilangan antara pesek dan alien. Faktanya, primata Madagaskar ini memiliki banyak kesamaan dengan kita. Untuk satu, mereka merasakan tekanan yang meningkat ketika habitat hutan mereka dihancurkan — dan penelitian baru menunjukkan bagaimana hidup di bawah tekanan konstan dapat membahayakan kelangsungan hidup mereka.
Konten terkait
- Apa Yang Bisa Diceritakan Lemur Tentang Penyakit Usus Manusia
- Bagaimana Cara Memilih Lemur dari Formasi? Perangkat Lunak Ini Membuat Lompatan
Lemur tikus adalah subkelompok lemur yang memiliki gelar primata terkecil di Bumi. Lemur tikus abu-abu ( Microcebus murinus ), yang berukuran hanya di bawah kaki dari hidung ke ekor dan beratnya sekitar dua ons, adalah spesies terbesar dalam kelompok itu. Saat ini dianggap sebagai spesies "Least Concern" oleh International Union for Conservation of Nature "Red List, " tetapi organisasi tersebut mencatat bahwa populasi lemur tikus abu-abu menurun karena sebagian besar hilangnya habitat.
Secara keseluruhan, lusinan spesies lemur Madagaskar telah lama menghadapi ancaman dari deforestasi dan perburuan oleh manusia. "Sudah diketahui bahwa spesies ini berada di bawah tekanan yang sangat tinggi dari kegiatan antropogenik dan hilangnya habitat, " Josué Rakotoniaina, seorang ahli ekologi di Universitas Georg-Agustus Göttingen, Jerman, mengatakan tentang pilihannya untuk meneliti primata mungil ini secara khusus. "Tapi tidak ada studi tentang bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi hewan-hewan ini secara ekologis."
Lemur tikus terbukti sangat bermanfaat bagi para ilmuwan yang mempelajari penyakit manusia, berkat ukurannya yang kecil (sekitar dua kali lipat ukuran tikus, dengan ekor hingga dua kali panjang tubuh mereka) dan kesamaan genetik dengan kita (mereka primata, seperti kita dan tidak seperti tikus). Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa mereka membuat model yang sempurna untuk melihat obesitas, penyakit mata, dan bahkan gangguan neurologis seperti penyakit Alzheimer dan demensia.
Rakotoniaina ingin melihat bagaimana tekanan yang ditimbulkan oleh tekanan lingkungan pada lemur ini berdampak pada hewan, terutama ketika menyangkut kelangsungan hidup dan reproduksi mereka. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa hormon yang dilepaskan ketika seseorang atau hewan non-manusia mengalami stres berguna dalam jangka pendek untuk melawan atau melarikan diri dari ancaman, baik dari pemangsa atau perkelahian jalanan, tetapi berbahaya secara fisiologis jika dialami dalam waktu lama. (Untuk lebih jelasnya, para peneliti menggunakan "stres" untuk berarti respons tubuh terhadap segala jenis situasi yang menyebabkan kesulitan, apakah itu ketakutan, kekurangan makanan atau tempat tinggal atau ketidakmampuan untuk menemukan jodoh.)
Hormon seperti kortisol — steroid yang ditemukan dalam darah, saliva, urin, rambut, dan kotoran manusia dan hewan lainnya — sering diukur oleh para ahli ekologi sebagai proksi untuk kesehatan sekelompok organisme. Tetapi sampel dari darah atau urin hanya menangkap tingkat stres pada titik waktu tertentu untuk hewan itu, sehingga sulit untuk menarik kesimpulan tentang stres jangka panjang berbahaya yang dihadapi organisme. Untuk mengatasi masalah itu, Rakotoniaina beralih ke sesuatu yang dimiliki sebagian besar mamalia: rambut.
Rambut memiliki banyak kualitas luar biasa. Untuk satu, ketika perlahan-lahan tumbuh, ia memelihara jejak-jejak kondisi dan lingkungan hewan dalam garis waktu yang kemudian dapat ditafsirkan oleh para ilmuwan, tidak seperti cincin pohon atau endapan atau inti es. Dengan mengambil sampel rambut dari lemur tikus abu-abu liar yang terperangkap dan dilepaskan, para ahli ekologi dapat melihat bagaimana kadar kortisol lemur berubah selama waktu pertumbuhan rambut-rambut itu, memberikan gambaran yang jauh lebih lengkap tentang stres jangka panjang yang dihadapi oleh binatang.
Dengan data dari rekan-rekannya di Pusat Primata Jerman, Rakotoniaina dapat memperoleh sampel rambut dan melacak populasi 171 lemur tikus abu-abu di Hutan Kirindy Madagaskar selama dua tahun mulai tahun 2012. Dengan menghubungkan kadar kortisol yang diukur dengan bagaimana lemur bernasib selama tahun-tahun itu, Rakotoniaina dan rekan-rekannya menemukan bahwa lemur yang menunjukkan kadar kortisol yang lebih rendah memiliki peluang rata-rata untuk bertahan hidup yang 13, 9 persen lebih tinggi daripada lemur dengan kadar kortisol yang lebih tinggi, menurut penelitian mereka yang diterbitkan hari ini di jurnal BMC Ecology .
Meskipun penelitian ini tidak mencoba mencari tahu bagaimana tingkat stres membuat lemur lebih kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup, Rakotoniaina berspekulasi bahwa itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemur yang stres lebih rentan terhadap penyakit dari sistem kekebalan yang melemah, dan lebih sedikit mampu bereaksi secara efektif dalam berbagai situasi kehidupan yang datang dengan stres normal.
Sebagai contoh, bagian dari penelitian melacak 48 lemur selama musim kawin mereka dan menemukan bahwa lemur yang tertekan, terutama yang jantan, memiliki peluang kematian yang lebih tinggi daripada rata-rata keseluruhan. Ini kemungkinan karena mereka tidak bisa menangani tekanan tambahan kawin di atas kelangsungan hidup. Rakotoniaina dan rekan-rekannya berencana untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya stres menyakiti lemur ini dengan melacak kesehatan mereka dari waktu ke waktu.
Dengan hasil ini, Rakotoniaina melihat kegunaan besar untuk sampel rambut yang mudah didapat dan non-invasif dalam mempelajari dinamika kesehatan dan populasi mamalia lain atau spesies lemur.
"Ini adalah kemajuan yang sangat besar di bidang ini, " kata Rakotoniaina, mencatat bahwa metode ini dapat digunakan oleh para konservasionis sebagai barometer yang akurat untuk memantau pelacakan hewan mereka dan apakah metode konservasi mereka bekerja secara efektif.
Michael Romero, seorang ahli biologi di Universitas Tufts yang meneliti fisiologi stres, mengatakan belum ada banyak penelitian yang mencoba menghubungkan respons hewan terhadap stres dengan kelangsungan hidupnya, dan penelitian yang dilakukan belum memiliki hasil yang konsisten.
Studi ini "adalah tambahan yang menarik untuk pekerjaan tentang peran respon stres dalam membantu hewan liar bertahan hidup di habitat alami mereka, " kata Romero, yang tidak terlibat dalam penelitian ini. Dia melihat penelitian baru sebagai langkah menuju memahami bagaimana peristiwa stres tertentu, terutama yang disebabkan oleh manusia, dapat berdampak pada kehidupan hewan.
Namun, Romero mengingatkan bahwa respons terhadap stres yang diukur oleh studi Rakotoniaina relatif kecil. "Apakah efek sekecil itu akan menjadi penanda yang andal masih merupakan pertanyaan terbuka, " katanya.